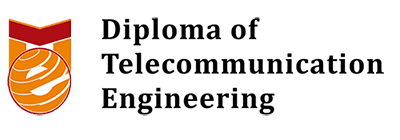Merdeka Belajar: Antara Gagasan Progresif dan Tantangan Implementasi
Dalam upaya mentransformasi sistem pendidikan nasional, pemerintah Indonesia memperkenalkan sebuah konsep revolusioner: Merdeka Belajar. Diinisiasi oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, gagasan ini bertujuan mendobrak sistem pendidikan lama yang kaku, birokratis, dan minim kreativitas. Namun, di balik semangat progresifnya, Merdeka Belajar juga menghadapi kenyataan kompleks di lapangan: mulai dari resistensi budaya sekolah, keterbatasan infrastruktur, hingga ketimpangan kompetensi guru.
Lalu, sejauh mana Merdeka Belajar berhasil mengubah wajah pendidikan Indonesia? Apakah ia sekadar jargon atau benar-benar menjadi titik awal perubahan?
Apa Itu Merdeka Belajar?
Secara esensial, Merdeka Belajar adalah sebuah filosofi pendidikan yang mengedepankan kebebasan berpikir, fleksibilitas dalam kurikulum, pembelajaran yang berpusat pada murid, serta otonomi bagi guru dan sekolah. Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan tantangan abad ke-21.
Beberapa inisiatif utama dalam payung Merdeka Belajar antara lain:
- Penghapusan Ujian Nasional (UN), diganti dengan Asesmen Nasional yang lebih menekankan pada literasi, numerasi, dan karakter.
- Penerapan Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel dan kontekstual.
- Platform Merdeka Mengajar yang mendukung pengembangan profesional guru.
- Kampus Merdeka, yang memberi mahasiswa ruang belajar di luar program studi utamanya, termasuk magang di industri.
Secara teori, ini adalah arah yang sangat visioner. Tapi seperti semua transformasi besar, implementasinya tidak semudah membalik telapak tangan.
Akar Permasalahan Pendidikan Indonesia
Sebelum membedah tantangan Merdeka Belajar, penting untuk memahami konteks mengapa perubahan ini diperlukan. Beberapa masalah mendasar dalam pendidikan Indonesia yang telah lama mengakar adalah:
- Sentralisasi Kurikulum: Selama bertahun-tahun, kurikulum dikendalikan secara terpusat, membatasi kreativitas guru dan tidak selalu relevan dengan konteks lokal.
- Budaya Belajar Menghafal: Sistem pendidikan sangat menekankan hasil ujian daripada proses berpikir dan kreativitas.
- Kesenjangan Kualitas Pendidikan: Ada perbedaan tajam antara pendidikan di kota besar dan daerah terpencil.
- Kompetensi Guru yang Belum Merata: Banyak guru belum mendapat pelatihan berkelanjutan yang sesuai dengan tantangan zaman.
Dalam konteks inilah Merdeka Belajar hadir sebagai upaya sistemik untuk memperbaiki struktur yang telah lama stagnan.
Gagasan Progresif di Balik Merdeka Belajar
Merdeka Belajar adalah bentuk desentralisasi pendidikan yang memberi ruang kepada sekolah untuk berinovasi dan kepada siswa untuk mengeksplorasi minatnya. Beberapa gagasan progresif yang diusung antara lain:
- Project-Based Learning (PBL): Siswa belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka.
- Profil Pelajar Pancasila: Karakter siswa didefinisikan berdasarkan nilai-nilai nasional seperti gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif.
- Diferensiasi Pembelajaran: Siswa dipandang sebagai individu unik dengan gaya belajar dan kebutuhan berbeda.
- Otonomi Guru: Guru diberi kebebasan menentukan metode mengajar yang paling efektif, tidak lagi sekadar mengikuti buku teks atau silabus kaku.
Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat dan keterampilan hidup yang relevan.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Namun, meskipun gagasannya sangat menjanjikan, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Tantangan implementasi Merdeka Belajar muncul dari berbagai arah:
1. Ketimpangan Infrastruktur dan Akses
Digitalisasi adalah bagian penting dari Merdeka Belajar. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah di daerah yang tidak memiliki internet, komputer, bahkan listrik yang stabil?
Banyak guru dan siswa di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) belum bisa memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar atau membuat portofolio belajar berbasis digital. Hal ini berpotensi memperbesar kesenjangan pendidikan nasional.
2. Kompetensi Guru yang Belum Siap
Kemandirian guru dalam menentukan metode mengajar hanya akan efektif jika mereka dibekali kemampuan pedagogik dan digital yang memadai. Namun, banyak guru masih terjebak dalam pola lama dan kurang terbiasa dengan pendekatan kreatif atau teknologi pembelajaran.
Meskipun program Guru Penggerak dan pelatihan daring sudah digalakkan, jangkauannya belum menjangkau seluruh pelosok, dan tantangan adaptasi tetap tinggi, terutama untuk guru berusia lanjut.
3. Beban Administratif dan Ketidakpastian Regulasi
Beberapa sekolah dan guru mengeluhkan bahwa kebijakan Merdeka Belajar tidak disertai dengan panduan teknis yang jelas dan terstruktur, sehingga menimbulkan kebingungan. Di sisi lain, masih banyak laporan bahwa beban administratif belum berkurang secara signifikan.
Ketika guru diharapkan menjadi kreatif dan inovatif, tapi tetap terbebani laporan harian yang panjang, maka tujuan Merdeka Belajar bisa menjadi kontraproduktif.
4. Resistensi Budaya Sekolah
Transformasi pendidikan juga terganjal oleh budaya konservatif di banyak sekolah, yang cenderung takut berubah. Beberapa kepala sekolah masih memegang teguh sistem lama dan ragu mengadopsi pendekatan baru karena dianggap “tidak aman” atau “belum terbukti”.
Sikap ini dapat menghambat adopsi inovasi yang justru dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan.
Kisah-Kisah Sukses: Bukti Merdeka Belajar Bisa Diwujudkan
Meski banyak tantangan, sejumlah sekolah dan guru telah membuktikan bahwa Merdeka Belajar bisa berjalan jika dilaksanakan dengan komitmen dan dukungan memadai.
- Di Yogyakarta, beberapa SMA telah menerapkan project-based learning lintas mata pelajaran yang menghasilkan karya inovatif seperti alat pertanian cerdas berbasis IoT.
- Di Bandung, komunitas Guru Penggerak menjadi motor perubahan yang memperkenalkan budaya belajar menyenangkan berbasis karakter dan eksplorasi minat.
- Di Papua, program Belajar di Radio berhasil menjangkau anak-anak di daerah tanpa internet, membuktikan bahwa pendekatan lokal tetap bisa masuk dalam semangat Merdeka Belajar.
Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa ketika guru diberdayakan, komunitas dilibatkan, dan pendekatan disesuaikan dengan konteks lokal, Merdeka Belajar bukan sekadar jargon.
Apa yang Perlu Diperkuat?
Agar Merdeka Belajar tidak berhenti sebagai ide indah semata, ada beberapa hal yang perlu diperkuat:
- Pendidikan dan pelatihan guru yang konsisten dan mendalam, bukan sekadar seminar sesaat.
- Peningkatan infrastruktur digital secara merata, termasuk subsidi perangkat dan jaringan.
- Penyederhanaan administrasi agar guru bisa fokus pada inovasi pembelajaran.
- Pemberdayaan kepala sekolah sebagai agen perubahan, bukan sekadar manajer administrasi.
- Monitoring dan evaluasi berbasis data, agar kebijakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Penutup: Menuju Pendidikan yang Membebaskan
Merdeka Belajar bukan sekadar slogan politik. Ia adalah sebuah visi besar untuk membebaskan pendidikan dari kungkungan sistem lama yang tidak relevan dengan masa depan. Ini adalah upaya menyelamatkan satu generasi dari pendidikan yang stagnan, menuju pendidikan yang hidup, menyala, dan memberi makna.
Namun, visi ini tidak akan terwujud tanpa kerja sama semua pihak: pemerintah, guru, sekolah, orang tua, akademisi, hingga pelaku industri. Dibutuhkan keberanian untuk berubah, kemauan untuk belajar ulang, dan komitmen untuk bertumbuh bersama.
Karena pada akhirnya, merdeka belajar adalah tentang merdeka berpikir, merdeka bertanya, merdeka berkreasi—bukan hanya bagi siswa, tapi juga bagi seluruh bangsa.
Refrensi : https://www.tempo.co/tag/merdeka-belajar