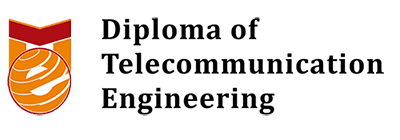Jalan Terjal Demokrasi: Menjelajahi Krisis Kepercayaan Politik di Indonesia
Demokrasi adalah sistem yang hidup dari partisipasi dan, yang paling penting, kepercayaan. Tanpa kepercayaan publik, institusi-institusi demokrasi akan kehilangan legitimasi, dan sistem itu sendiri berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa substansi. Di Indonesia, setelah lebih dari dua dekade reformasi, demokrasi kita dihadapkan pada jalan terjal. Di balik gemuruh pemilu, hiruk-pikuk parlemen, dan janji-janji politik, kita merasakan adanya erosi, sebuah krisis kepercayaan politik yang membayangi masa depan bangsa.

Di Balik Tirai: Mengapa Kepercayaan Publik Meredup?
Krisis kepercayaan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari berbagai faktor dan masalah yang telah mengakar dalam sistem politik kita.
1. Korupsi yang Tak Berujung dan Impunitas
Korupsi adalah penyakit kronis yang menggerogoti setiap sendi kehidupan berbangsa, dan menjadi penyebab utama merosotnya kepercayaan publik. Mulai dari kasus-kasus mega korupsi yang melibatkan pejabat tinggi hingga praktik suap di level birokrasi, semua meninggalkan luka mendalam. Masyarakat melihat bagaimana uang rakyat diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sementara penegakan hukum terhadap pelaku korupsi seringkali dinilai tebang pilih atau menghasilkan vonis yang ringan. Ketika keadilan tidak ditegakkan secara imparsial, rasa frustrasi dan sinisme publik pun meningkat. Impunitas atau perasaan bahwa pelaku korupsi bisa lolos tanpa hukuman setimpal, semakin memperparah krisis kepercayaan.
2. Oligarki dan Politik Dinasti: Kekuatan di Balik Layar
Reformasi diharapkan mengakhiri dominasi kekuasaan di tangan segelintir elite. Namun, yang terjadi justru munculnya oligarki baru yang menguasai sumber daya ekonomi dan politik. Kelompok-kelompok ini, seringkali terkait dengan kepentingan bisnis besar, memiliki pengaruh kuat dalam pembuatan kebijakan dan penentuan calon-calon pejabat.
Fenomena politik dinasti juga kian marak, di mana kekuasaan diwariskan atau diputar di antara anggota keluarga. Ini menunjukkan bahwa kesempatan berpolitik tidak setara, menutup ruang bagi individu-individu kompeten di luar lingkaran elite, dan memperkuat kesan bahwa politik adalah ajang perebutan kekuasaan, bukan pengabdian.
3. Lemahnya Institusi Demokrasi dan Hukum
Institusi-institusi pilar demokrasi seperti parlemen, partai politik, lembaga peradilan, dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seringkali menjadi sasaran kritik.
- Parlemen: Sering dinilai kurang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, bahkan terkadang menjadi arena transaksional.
- Partai Politik: Kehilangan fungsi sebagai jembatan aspirasi rakyat, lebih berorientasi pada kepentingan elite partai, dan proses rekrutmen politik yang tidak transparan.
- Lembaga Peradilan: Isu suap hakim, intervensi politik, dan putusan yang kontroversial merusak citra keadilan.
- KPK: Pelemahannya melalui revisi undang-undang dan serangkaian isu internal menimbulkan kekhawatiran publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
Ketika institusi-institusi ini kehilangan independensi dan integritasnya, masyarakat kehilangan saluran untuk menyuarakan aspirasi dan mencari keadilan.
4. Polarisasi Politik dan Politik Identitas
Terutama sejak Pemilu 2014 dan 2019, politik Indonesia cenderung mengalami polarisasi yang tajam. Masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu yang saling berhadapan, seringkali didorong oleh politik identitas yang mengeksploitasi sentimen agama, etnis, atau kelompok. Media sosial menjadi arena penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian yang memperdalam jurang pemisah. Polarisasi ini menghambat konsolidasi demokrasi, merusak kohesi sosial, dan membuat dialog konstruktif menjadi sulit.
5. Rendahnya Pendidikan Politik dan Literasi Digital
Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang fungsi demokrasi, peran lembaga negara, dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Rendahnya pendidikan politik membuat mereka rentan terhadap manipulasi, janji-janji populis, dan kampanye hitam. Di era digital, rendahnya literasi digital juga menyebabkan masyarakat mudah terpapar informasi yang tidak akurat, memperburuk polarisasi, dan mengurangi kemampuan mereka untuk membuat keputusan politik yang rasional.
6. Komunikasi Politik yang Buruk dan Janji Palsu
Para politisi dan pejabat seringkali gagal dalam membangun komunikasi yang jujur dan transparan dengan publik. Janji-janji politik yang terlalu muluk saat kampanye seringkali tidak terealisasi setelah menjabat, menyebabkan kekecewaan dan memperkuat stigma bahwa politisi hanya mencari kekuasaan. Kurangnya akuntabilitas dan responsivitas terhadap kritik masyarakat juga memperparah kondisi ini.
Dampak Krisis Kepercayaan: Ancaman Tersembunyi bagi Demokrasi
Krisis kepercayaan politik tidak berhenti pada rasa kecewa semata, tetapi memiliki dampak serius bagi kesehatan demokrasi itu sendiri.
1. Partisipasi Politik yang Menurun (Atau Sekadar Formalitas)
Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada sistem politik, motivasi untuk berpartisipasi pun menurun. Angka partisipasi pemilu mungkin masih tinggi, tetapi partisipasi ini bisa jadi hanya formalitas tanpa diiringi sense of ownership terhadap proses demokrasi. Mereka mungkin memilih karena desakan atau apatisme, bukan karena keyakinan. Partisipasi di luar pemilu, seperti kontrol sosial atau pengawasan kebijakan, juga melemah.
2. Kualitas Kebijakan yang Menurun
Dengan rendahnya partisipasi dan kontrol publik, para pembuat kebijakan cenderung tidak merasa terikat untuk merumuskan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat. Keputusan-keputusan bisa lebih didikte oleh kepentingan elite atau kelompok tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Ini dapat menghasilkan kebijakan yang tidak efektif, tidak adil, atau bahkan merugikan publik.
3. Bangkitnya Populisme dan Otoritarianisme
Krisis kepercayaan dapat menciptakan lahan subur bagi munculnya pemimpin-pemimpin populis yang menjanjikan solusi instan dan mengklaim sebagai “penyelamat” dari sistem yang korup. Mereka seringkali menyerang institusi demokrasi, melemahkanChecks and Balances, dan memecah belah masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengarah pada kemunduran demokrasi atau bahkan kebangkitan otoritarianisme.
4. Stabilitas Sosial yang Terganggu
Jika masyarakat tidak lagi percaya pada institusi politik sebagai saluran penyelesaian masalah, mereka mungkin mencari jalan lain, termasuk melalui aksi-aksi jalanan, konflik horizontal, atau bahkan tindakan kekerasan. Ini dapat mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Meniti Jalan Terjal: Membangun Kembali Kepercayaan
Membangun kembali kepercayaan politik bukanlah tugas yang mudah atau instan. Ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan upaya kolektif dari semua elemen bangsa.
1. Perkuat Penegakan Hukum dan Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Ini adalah langkah paling krusial. Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK) harus independen, profesional, dan berani menindak koruptor tanpa intervensi atau pilih kasih. Hukuman yang tegas dan efek jera harus diterapkan. Pemulihan aset hasil korupsi juga penting untuk mengembalikan kerugian negara.
2. Reformasi Partai Politik dan Sistem Pemilu
Partai politik harus direformasi agar lebih transparan dalam pendanaan, rekrutmen calon, dan pengambilan keputusan. Sistem pemilu harus dirancang untuk mengurangi money politics dan meningkatkan akuntabilitas calon terpilih. Perluasan kesempatan bagi non-elite untuk berkompetisi secara adil juga penting.
3. Perkuat Checks and Balances dan Lembaga Demokrasi
Institusi seperti parlemen, lembaga peradilan, dan lembaga independen harus diperkuat independensinya dan kapasitasnya untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Pelemahan terhadap lembaga-lembaga ini, seperti yang terjadi pada KPK, harus dihindari.
4. Pendidikan Politik dan Literasi Digital yang Masif
Pendidikan politik harus dimulai sejak dini dan terus menerus di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara. Program literasi digital juga harus digalakkan untuk melawan hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian, serta mendorong penggunaan media sosial yang bertanggung jawab.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Pemerintah harus lebih transparan dalam setiap pengambilan keputusan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan program. Mekanisme akuntabilitas harus diperkuat, dan kritik dari masyarakat harus dilihat sebagai masukan konstruktif. Keterbukaan informasi publik adalah kunci.
6. Mendorong Peran Aktif Masyarakat Sipil dan Media
Organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting sebagai pengawas, advokat, dan jembatan aspirasi. Media massa yang independen dan berintegritas juga krusial dalam menyajikan informasi yang akurat dan melakukan kontrol terhadap kekuasaan.
Demokrasi di Indonesia telah menempuh perjalanan yang panjang dan berliku. Krisis kepercayaan politik adalah alarm yang harus kita dengar dan respons. Ini bukan akhir dari demokrasi, melainkan tantangan untuk membuatnya lebih matang, responsif, dan benar-benar melayani kepentingan rakyat. Membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen dari semua pihak. Hanya dengan fondasi kepercayaan yang kokoh, demokrasi kita bisa benar-benar menjadi kuat, adil, dan berkelanjutan untuk masa depan bangsa.
Menurut Anda, di antara semua tantangan ini, masalah mana yang paling mendesak untuk diatasi agar kepercayaan politik di Indonesia dapat pulih kembali?
Link Refrensi : https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/03/jalan-terjal-demokrasi-indonesia